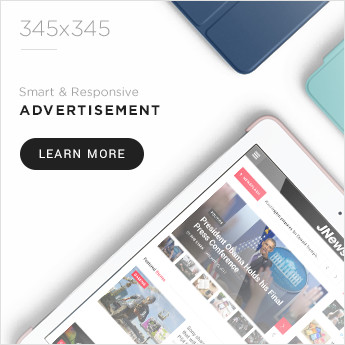MAKASSAR, LINKSATUSULSEL.COM–Ada keletihan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ketika kita mencoba menjelaskan kebenaran kepada orang yang menolak berpikir. Imam Syafi’i, ulama besar yang dikenal karena keluasan ilmunya dan ketajaman logikanya, suatu kali mengakui bahwa yang paling sulit dihadapi bukanlah lawan debat yang pandai, melainkan yang bodoh—mereka yang menolak mendengar, apalagi memahami.
Ungkapan itu bukan bentuk arogansi intelektual, melainkan refleksi tentang batas komunikasi. Sebab dialog sejati hanya lahir ketika dua pikiran terbuka, saling mencari makna dan kebenaran. Tanpa itu, perdebatan berubah menjadi kebisingan yang tak berujung—lebih menyerupai pertunjukan ego daripada pencarian hikmah.
Dari Madinah ke Athena
Menariknya, jauh di luar tradisi Islam, filsafat Yunani kuno melalui aliran Stoikisme juga memandang hal yang serupa. Epictetus, seorang filsuf budak yang kemudian dihormati karena kebijaksanaannya, pernah berkata: “Adalah tanda kebodohan ketika seseorang mencoba mengubah hal yang berada di luar kekuasaannya.”
Inilah yang disebut sebagai Dichotomy of Control: prinsip bahwa kita hanya dapat mengendalikan pikiran dan tindakan kita sendiri, bukan reaksi atau opini orang lain. Berusaha meyakinkan seseorang yang menolak berpikir sama saja dengan mencoba menenangkan badai dengan bujuk rayu.
Bagi kaum Stoik, kebijaksanaan bukan diukur dari seberapa banyak argumen yang kita menangkan, tetapi dari sejauh mana kita mampu menjaga ketenangan batin di tengah kebodohan orang lain.
Antara Logika dan Ego
Dalam setiap perdebatan, selalu ada dua jalan: mencari kebenaran atau mempertahankan harga diri. Orang berilmu memilih yang pertama, sementara yang bodoh sering terjebak pada yang kedua. Di sinilah letak kebuntuan itu—karena kebenaran tak mungkin tumbuh di tanah yang disirami oleh ego.
Marcus Aurelius, kaisar-filsuf Romawi, pernah menulis dalam Meditations: “Jika seseorang berbuat salah, ajari dia dengan sabar. Jika ia menolak diajari, biarkan dia dengan kesalahannya.”
Nasihat itu terdengar lembut, tapi sesungguhnya keras kepala dalam kebaikan. Aurelius tahu, tidak semua manusia siap menerima cahaya, dan memaksa mereka hanyalah bentuk kesombongan terselubung—seolah kita adalah juru selamat bagi kebodohan orang lain.
Menjaga Kewarasan di Tengah Kebisingan
Dalam dunia yang riuh oleh komentar, unggahan, dan perdebatan tanpa ujung di media sosial, kebijaksanaan Imam Syafi’i dan para filsuf Stoik terasa semakin relevan. Kita hidup di zaman ketika banyak orang berbicara bukan untuk memahami, tetapi untuk memenangkan tepuk tangan digital.
Berdebat dengan orang bodoh di dunia maya sama seperti berteriak di dalam ruang gema: suara kita kembali kepada diri sendiri, tanpa pernah sampai ke telinga lawan bicara. Dalam situasi seperti ini, diam bukan lagi tanda kelemahan, melainkan pilihan strategis untuk menjaga kewarasan.
Seneca, filsuf Romawi yang hidup sezaman dengan Nero, menulis dengan getir: “Jangan masuk ke arena di mana kemenangan tidak memberi kehormatan.” Sebab ada pertempuran yang tidak patut dimenangkan—karena bahkan kemenangan di dalamnya justru mengikis martabat kita.
Kemenangan yang Sunyi
Stoikisme mengajarkan tentang ataraxia—ketenangan jiwa yang tidak tergoyahkan oleh ombak luar. Imam Syafi’i pun mencontohkan hal yang sama dalam konteks spiritual: memilih diam, bukan karena tak mampu menjawab, tetapi karena sadar bahwa jawaban tidak akan mengubah apa pun.
Keduanya, meski lahir dari peradaban dan keyakinan yang berbeda, bertemu pada satu titik: kebijaksanaan sejati bukanlah kemampuan untuk mengalahkan orang lain, melainkan kemampuan untuk menguasai diri sendiri.
Maka ketika berhadapan dengan orang yang menolak berpikir, berdiam bukan berarti kalah. Itu adalah bentuk tertinggi dari kemenangan—kemenangan menjaga akal sehat, waktu, dan kedamaian hati.
Karena pada akhirnya, seperti kata Imam Syafi’i, berdebat dengan orang bodoh hanyalah cara tercepat untuk kehilangan kedamaian, bukan untuk menemukan kebenaran.(*)
Penulis Mazhud Azikin